Nomenklatur “Islam†Kita
- 11 Februari 2015
- 00:00 WITA
- Nasional
- Dibaca: 5590 Pengunjung

Opini, suaradewata.com- Aksi terorisme acapkali identik dengan agama Islam. Hal semacam ini, sepintas lalu benar manakala penafsiran kata ‘jihad’ masih mengarah pada kondisi di mana Nabi Muhammad dan pengikutnya mempertahankan diri atas pelbagai serangan yang dilakukan non-muslim terhadap benih cikal-bakal agama Islam di kota Madinah. Padahal, masih banyak pemaknaan yang lebih tepat dan sesuai terhadap kata ‘jihad’ tersebut dalam konteks seperti sekarang.
Para sejarawan Islam banyak mengemukakan dalam konteks peperangan itu sesuatu yangsantun. Bahwa peperangan yang dilakukan Nabi dan kelompoknya lebih bersifat mempertahankan diri. Perang Nabi Muhammad dan pengikutnya merupakan usaha untuk mencapai perdamaian, sehingga dalam peperangan tersebut jangan sampai prajuritnya melupakan nilai-nilai kemanusiaan yang seluhur-luhurnya. Sebuah hadist riwayat Bukhori-Muslim misalnya menyatakan, “Jika seseorang di antara kamu terlibat dalam peperangan, maka hendaknya yang bersangkutan menghindari wajah”. Nabi berpesan karena pada wajah seseorang terdapat nilai kehormatan.
Dalam kaitannya memaknai kata ‘jihad’ dewasa ini, penggunaan kekerasan sebagai sarana yang dipakai cenderung menjauhi inti yang ingin disampaikan setiap agama, terkecuali Islam. Jihad dalam bentuknya yang positif jauh lebih rumit dan sulit ketimbang menggunakan cara-cara negatif. Realita yang mudah ditemui di tengah-tengah masyarakat muslim dunia seperti sekarang ini, terekam kekurangan kebutuhan pokok meliputi sandang, pangan, papan dan kesehatan.Penyelesaian masalah serius semacam ini merupakan warisan keteladanan Nabi yang sangat luar biasa dan patut diutamakan.
Menjadi tidak elegan ketika sebagian orang dengan pemahaman keislaman yang ke kanak-kanakan malahan menjatuhkan citra yang sejak lama dibangun sebagai cita-cita agama Islamyang rahmatanlilalamin.
Gesekan
Persinggungan Islam dan Barat telah terjadi sejak lama. Persoalannya semakin meruncing di era modern dan puncaknya pada 11 September 2001 lewat tragedi pengeboman gedung WTC yang diduga didalangi golongan Islam fundamentalis. Isu terorisme dan Islam menjadi sangat erat ketika pemimpin negara –Amerika Serikat-- yang berkuasa pada saat itu memandang tidak secara keseluruhan ajaran-ajaran agama Islam. Lewat bahasa yang sederhana, anggapan bahwa Islam satu-satunya agama yang mendidik dan melahirkan terorisme.
Isu terorisme bisa dicermati lewat karya Samuel P. Huntington pada dasawarsa 1996. Ia memprediksi bahwa pasca-perang dingin, masyarakat dunia akan mengalami “clash of civilizations” (benturan antar peradaban). Bagi Huntington, relasi serta hubungan antar-negara dan kelompok-kelompok tidak berjalan mulus, bahkan akan sering terjadi hubungan yang bersifat antagonistik.
Pada level yang ruang lingkupnya kecil, Islam akan saling bersinggungan juga terjadi benturan dengan ortodoksnya, Hindu, bangsa Afrika, dan kelompok-kelompok Kristen Barat. Sedangkan dalam skala yang besar, benturan dan konflik akan terjadi antara negara-negara Barat di satu pihak, dengan Islam dan masyarakat Asia di pihak lain. Masalah yang paling berbahaya tentu konflik peradaban Islam dan Barat yang dipicu sikap-sikap arogansi negara-negara Barat dan sikap-sikap Islam ortodoks-fundamental-radikal.
Terkait konfliks Islam dan Barat yang diungkapkan Huntington tersebut, ada proses di mana kelompok Islam yang menganggap pengembangan institusi –bukan budaya Islam—merasa khawatir jangan-jangan Islam akan kehilangan kebesarannya. Pada titik inilah romantisme masa lalu dijadikan acuan tanpa mempelajari dan memahami maksud agama Islam diturunkan.
Sebenarnya ketakutan kelompok Islam akan ketertinggalan dari negara Barat yang menjadi motif bagi terorisme. Diperkirakan dengan melakukan hal semacam itu, pihak-pihak lain akan “ketakutan” pada Islam sehingga akan menjauh dari kelompok-kelompok muslimin, dan dengan keterpisahan itu kaum muslimin akan aman dari “gangguan”. Sikap seperti itu merupakan bukti dari kekerdilan jiwa dan kurangnya pengetahuan akan proses sejarah (Abdurrahman Wahid, 2006).
Islam Kita
Secara keseluruhan, mempelajari masyarakat muslimin dapat diklarifikasikan dan dibedakan menjadi dua garis besar pendekatan: pertama, pengetahuan dan capaian masyarakat Islam secara kultural (Budaya). Dan kedua, capaian secara kelembagaan (institutional). Diantara kedua pendekatan ini mempunyai kelemahan, dalam pendekatan awal akan kita temui carut-marutnya dan tidak terkonsepnya kelompok yang menitikberatkan pada pendekatan kultural, sebut saja dalam contoh dalam hal ini adalah NU (Nahdlatul Ulama’).
Adapun pendekatan terakhir akan berakibat fatal, lantaran yang terlihat hanya memenuhi ambisi-ambisi pribadi, seperti lembaga ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) misalnya.Dari kedua pendekatan itu, umat Islam khususnya di Indonesia harus mencapai keseimbangan antara kedua pendekatan di atas dalam sebuah masyarakat yang majemuk. Pencapaian secara kultural maupun institutional yang tidak saja lewat budaya akan tetapi juga melalui lembaga yang terorganisir. Sehingga, melalui kedua proses ini akan dicapai hasil yang optimal secara teoritik.
Lebih lanjut dalam memahami munculnya benih-benih terorisme di Indonesia, di samping tekanan global seperti yang disebutkan di atas, juga tak bisa lepas dari realitas mengkristalnya politik aliran. Dalam berpolitik misalnya kalangan “santri” cenderung berafiliasi pada partai-partai Islam. Sedangkan kelompok “abangan” lebih menghimpun suara dan gerakannya terhadap partai-partai beraliran sekuler. Fenomena politik aliran semacam ini, memicu tumbuhnya kelompok-kelompok dalam masyarakat yang beraliran keras yang sering ditengarai sebagai kelompok Islam fundamentalis.
Pensyari’atan islam sebagai dasar negarayang tidak kunjung terpenuhi serta ruang lingkup artikulasi politik yang kurang tersalurkan dalam kancah pemerintahan menjadi agenda pengukuhan aksi terorisme di Indonesia. Lihat saja amandemen 1945, undang-undang, peraturan daerah, opini publik serta teror dalam kurun waktu berkembangnya isu Piagam Jakarta yang diperjuangkan pada Sidang Tahunan MPR 1-11 Agustus 2002 dan berakhir dengan tidak terakomodirnya tuntutan-tuntutan Piagam Jakarta tersebut, menjadi bukti sejarah perhimpunan dan pergerakan kelompok fundamentalis di Indonesia.
Namun, yang patut menjadi perhatian pemerintah sebenarnya bukan pada keberadaan kelompok atau golongan fundamentalis dengan paham dan ideologinya, bukan juga dalam pada hak-hak mereka melakukan manuver-manuver memperjuangkan politik mereka. Tetapi pemerintah harus memperhatikan juga mempersoalkan cara-cara yang digunakan dan dampaknya yang sering kali disinyalir berbau kekerasan.
Dalam mengambil tindakan tegas tersebut, pemerintah juga jangan sampai melupakan kebebasan berpendapat setelah sekian lama masyarakat Indonesia terkungkung seperti ketika orde baru. Terlebih, pemerintah dengan kekuatan militer yang ada jangan sampai melakukan tindakan kekerasan terhadap masyarakat sipil. Kebebasan yang terkontrol harus menjadi ciri pemerintah dalam memberi ruang sekaligus batasan-batasan bagi kelompok-kelompok fundamentalis-radikal. Upaya ini, diharapkan menekan aksi terorisme yang cenderung merasa terkebiri hak berpendapat dan politiknya.
Nur Wahid Wijoyo, penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial Keagamaan















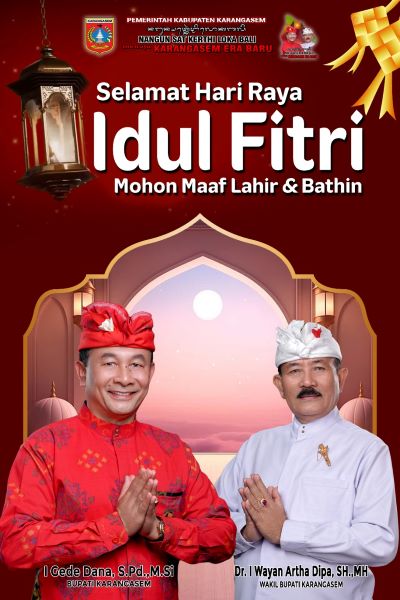


















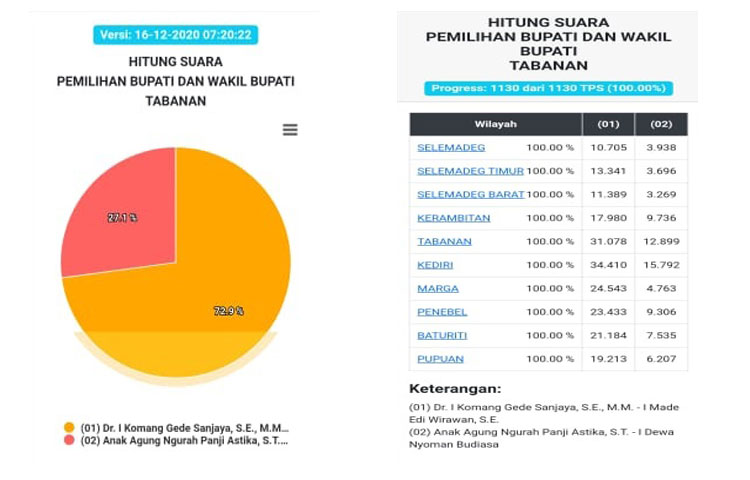































Komentar