Pancasila Ditengah Kepungan Iseme-isme dan LGBT
- 02 Oktober 2015
- 00:00 WITA
- Nasional
- Dibaca: 2255 Pengunjung

Opini, suaradewata.com- Setiap 1 Oktober, kita sebagai bangsa Indonesia selalu memperingati Hari Kesaktian Pancasila, sebagai momen bersyukur bangsa ini yang terhindar dari perpecahan dalam negeri, karena ada Pancasila sebagai ideologi pemersatu. Berbicara tentang ideologi negara, maka kita tidak dapat main-main dan harus serius memikirkannya, apalagi di era saat ini yang marak dengan proxy war. Ideologi tidak boleh hanya menjadi wacana, namun ideologi harus dapat menjadi nilai dan membentuk karakter bangsa.
Selama ini, “kecintaan” kita terhadap Pancasila terlalu “over dosis” sehingga seringkali menerjemahkan dan melaksanakan Pancasila menurut ukurannya masing-masing. Efeknya Pancasila saat ini kurang dikenal oleh generasi muda, terbukti dengan hasil survei tahun 2013 terhadap 100 siswa SMA di Depok, Jabar, terungkap 71 siswa tidak hafal kelima sila Pancasila, dan hanya 11 siswa yang hafal (Harian Singgalang, 28 September 2015 halaman A-6). Kemungkinan besar di daerah lainnya ditemukan fenomena serupa.
Salah satu contoh “over dosis” kecintaan terhadap Pancasila antara lain pada era Orde Lama dan konsep Presiden Soekarno tentang sistem Demokrasi Terpimpin banyak menuai kritik, baik dari partai politik seperti Masyumi (Muhammad Natsir), PSI (Syahrir), dan Partai Katolik (J. Kasimo) maupun dari Wakil Presiden Muhammad Hatta. Dengan kebijakan politik Demokrasi Terpimpin, Soekarno diangkat sebagai presiden seumur hidup dan sebagai pemimpin besar revolusi. Pengultusan Soekarno dengan pengangkatan presiden seumur hidup dan pemimpin besar revolusi jelas menunjukkan karakter feodalistik, otoriter, dan sentralistik, yakni sebagai ciri “masyarakat warisan”. Hal itu mengindikaikan telah terjadi salah tafsir dan penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD 1945.
Era Orde Lama juga ditandai dengan berbagai kritik daerah atas sentralisasi pembangunan di pusat (Gongggong, 2002a:xxi). Muhammad Hatta, akhirnya mengundurkan diri sebagai “dwi tunggal” pada akhir 1956. Tuntutan desentralisasi yang disuarakan daerah-daerah tidak digubris, akhirnya berkembang menjadi pemberontakan, dan ditanggapi dengan operasi militer secara draconian (keras dan kejam)(Kahin, 2005), seperti dalam kasus PRRI-Permesta. Itu sebabnya dikatakan bahwa Pancasila dikubur sendiri oleh penetusnya (HAMKA, 2015: 51).
Pada masa Orde Baru, slogan yang dikibarkan adalah “melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen”. Pancasila ditafsirkan oleh pemerintah, tidak boleh ada alternatif penafsiran lain dan berbeda. Dalam proses indoktrinasi, Pancasila dan UUD 1945 selalu digambarkan sebagai karya agung yang “amat sempurna”, suci, dan sakral, dan “kelemahan-kelemahan yang terdapat di dalamnya justru dibalik menjadi kekuatannya” (Gonggong, 2002b:42). Stabilitas nasional (pemerintahan dan keamanan) adalah “harga mati” demi keberlangsungan pembangunan (terutama di bidang ekonomi) yang disusun dalam tahapanan-tahapanan model W. W. Rostow, yakni melalui tahapanpelita-pelita menuju masyarakat tinggal landas (Abraham, 1991:31-51).
Pada era ini, Pancasila diperlihatkan sebagai momok kaku yang menakutkan. Efek dari perlakuan terhadap Pancasila di atas adalah “pengucilan” Pancasila selama 17 tahun “Orde Reformasi”. Hal itu dimulai dengan pembubaran BP7 dan pencabutan Tap-MPR No. 2 tahun 1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (melalui Tap MPR No 18 Tahun 1998), penggugatan atas asas tunggal Pancasila, penghilangan mata pelajaran PMP, Mata Kuliah Pancasila, dan eforia kebebasan dan pembebasan begitu diagungkan. Di samping itu, pemerintah pada masa Orde Reformasi ini juga menerapkan kebijakan otonomi daerah (yang sesungguhnya telah disuarakan oleh daerah pada masa Orde Lama yang memicu pergolakan PRRI/ Permesta). Walaupun demikian, menurut Saifuddin, pelaksanaan kebijakan otonomi daerah menimbulkan persoalan-persoalan baru dalam konteks integrasi nasional. Hal itu disebabkan otonomi daerah yang bertujuan menciptakan keadilan melalui pelimpahan kekuasaan politik dan ekonomi ke daerah-daerah ternyata meningkatkan primordialisme baru di berbagai daerah yang cenderung kontra produkti (Saifuddin, 2005:364-365).
Kepungan Isme-Isme dan LGBT
Diluar komunisme dan radikalisme, sebenarnya ada banyak isme yang berkembang selama ini seperti atheisme, fundamentalisme, nasionalisme, imperialisme, kolonialisme, sosialisme, kapitalisme, liberalisme, feodalisme, militerisme, fasisme, terorisme, separatisme, eksistensialisme, plagiarisme, indivudialisme, hedonisme, dsb... dsb... Isme yang sudah lama ada, terkadang terus mengalami pembaruan dan kemudian dikenali sebagai kategorisasi isme baru, dengan menambahkan frase neo di depannya. Selain istilah-istilah isme yang mendunia, tidak terkecuali penggunaan istilah isme sampai-sampai juga digunakan di dalam masyarakat kita seperti ABSisme, ndoroisme, asbunisme, cuapisme, dll yang masih akan tumbuh tambah lagi. Yapi Tambayong (2013), seorang budayawan yang dikenal juga dengan nama Remy Sylado, bahkan menulis buku berjudul Kamus Isme-Isme dengan menuangkan isme-isme dari A - Z berjumlah 953 isme dari istilah isme yang mendunia hingga yang dikenali secara khas hanya ada di Indonesia. Semua isme ini sebenarnya sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, dan pendukung isme-isme ini berupaya terus menggoyang Pancasila.
Dalam penyebaran isme apapun, yang selalu menjadi target adalah kelompok pemuda, sehingga tidak jarang kita menemukan fakta tentang keterlibatan kaum muda dalam paham komunisme ataupun radikalisme di era reformasi dan zaman medsos seperti sekarang ini, hal ini bisa juga dijelaskan sebagai perwujudan dari perilaku yang disebut sebagai aksi identitas. Sebagaimana dinyatakan oleh Marranci (2006, 2009) bahwa aksi identitas (act of identity) itu adalah suatu upaya untuk merespon dan mengatasi “krisis identitas” yang dialami kaum muda baik pada tingkatan individu maupun kolektif di tengah-tengah perubahan yang berlangsung drastis dalam transisi demokrasi. Berkenaan dengan ini kaum muda (youth) dikatakan berkecenderungan lebih kuat dan berkemungkinan lebih besar untuk berpartisipasi dalam paham radikalisme dibandingkan orang dewasa (adult). Menurut hemat kami, inipun dapat berlaku dalam komunisme.
Sidney Jones memiliki analisis tersendiri. Menurutnya, radikalisme itu bukan hanya berpotensi muncul dalam praktik sistem politik negara otoriterian, tetapi juga berpotensi muncul dalam praktik sistem politik demokrasi. Jones bahkan menegaskan bahwa di Indonesia potensi radikalisme Islam itu sungguhlah nyata ada, meskipun hanya minoritas penganutnya, dan walaupun minoritas juga yang berkecenderungan memilih cara-cara kekerasan dalam memperjuangkan paham keyakinan keIslamannya. Dalam hal ini menurut hemat kami komunisme pun sama saja, bisa tumbuh kembang dalam sistem politik otoriterian mapun demokrasi, meski bedanya dengan radikalisme agama, ia tidak dilandaskan pada paham keyakinan agama.
Diluar itu, Pancasila juga menghadapi ancaman dari isme baru yang oleh komprador asing di Indonesia ataupun pihak lainnya diupayakan untuk menjadi isme global selaras dengan demokratisasi dan HAM. Isme tersebut adalah kelompok pendukung lesbian, gay, biseks dan transgender (LGBT). Fenomena LGBT jelas bertentangan dengan Pancasila, dan dalam upaya “menyosialisasikan” masalah ini pendukung LGBT melakukannya dengan beragam cara, seperti salah satu acara kontestasi musik di USA yang dimenangkan penyanyi transgender, referendum UU pengesahan pernikahan sejenis di Australia, serta ada rumors telah terjadi pernikahan sejenis belum lama ini di salah satu kabupaten di Bali.
Ditengah-tengah kepungan isme-isme tersebut, sebenarnya Pancasila “belum tamat” dan masih “sakti”. Namun, tetap harus ada upaya mempertahankan Pancasila yang sebenarnya merupakan sebuah keniscayaan. Upaya tersebut antara lain pentingnya reideologisasi Pancasila atau memperkenalkan kembali Pancasila kepada generasi muda tidak dengan indoktrinasi, namun dengan cara-cara kekinian. Disamping itu, perlu memproteksi Pancasila dengan undang-undang, karena selama ini hanya ada produk politik yang melindungi Pancasila yaitu Tap MPRS Nomor XXV/1966, namun sebagai keputusan politik, maka tidak dapat digunakan untuk keperluan law enforcement, sehingga aparat penegak hukum dalam menghadapi fenomena maraknya pemakai lambang “palu arit” di beberapa daerah misalnya, hanya dapat diamankan dengan alasan meresahkan masyarakat, bukan dengan alasan mengancam Pancasila. Sejatinya, kalau dianalogikan maka kita harus memandang Pancasila sebagai aset seperti umpamanya rumah, mobil, lahan pertanian dll yang dilindungi secara hukum melalui kepemilikan rumah, BPKB dll, sehingga tidak ada yang berani mengambil dan merusaknya, bahkan tidak bodong secara hukum.
Jika Pancasila dapat diimplementasikan secara baik, maka revolusi mental dalam upaya menciptakan karakter bangsa tidak akan sulit direalisasikan. Apa sih karakter bangsa itu? Menurut Koentjaraningrat, untuk benar-benar menjadi suatu bangsa ada beberapa tantangan karakter bangsa yang harus dimiliki dan dijaga, yaitu: (1) sifat menghargai, (2) kesabaran untuk meniti usaha dari awal, (3) adanya rasa percaya diri karena yakin dirinya berkualitas, (4) sikap disiplin dalam waktu dan pekerjaan, (5) sifat mengutamakan tanggung jawab. Dalam rangka membangun karakter bangsa itu Koentjaraningrat juga mencatat adanya beberapa sikap mental bangsa Indonesia yang bisa menjadi penghambat pembangunan, seperti: (1) sikap mental yang meremehkan mutu dan rendahnya semangat berkompetisi, (2) sikap mental tidak percaya kepada diri sendiri, sebaliknya cenderung lebih percaya pada apa yang dihasilkan orang lain atau negara lain, (3) sikap mental tidak disiplin, suka mengulur-ulur waktu, dan (4) sikap mental suka menerabas, suka mencari jalan gampang dan membenarkan segala cara. Hal-hal inilah kiranya yang terlebih dahulu harus didobrak bersama agar tidak mengungkung kita mengaktualisasikan ideologi Pancasila. Dengan kata lain, kita tidak saja perlu mengantisipasi ancaman eksternal, tapi hendaknya juga harus aware mengatasi rintangan internal. Sebab, akumulasi karakter bangsa yang belum mantap dan adanya rintangan mental tersebut justru bisa juga menjadi celah atau lubang angin bagi komunisme dan radikalisme yang sejatinya tidak kita inginkan. Dirgahayu Pancasilaku.
Toni Ervianto, Penulis adalah alumnus Fisip Universitas Jember dan alumnus pasca sarjana, Universitas Indonesia (UI). Tinggal di Jakarta.









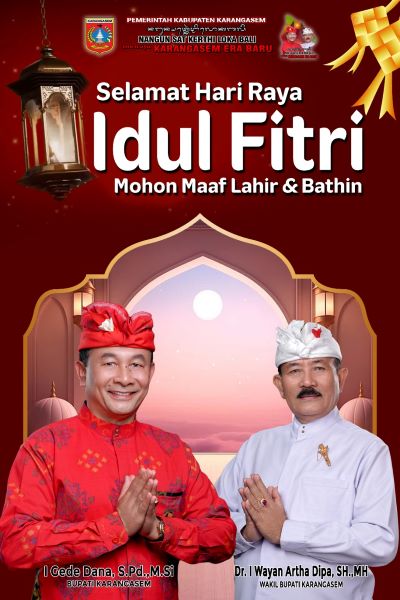


















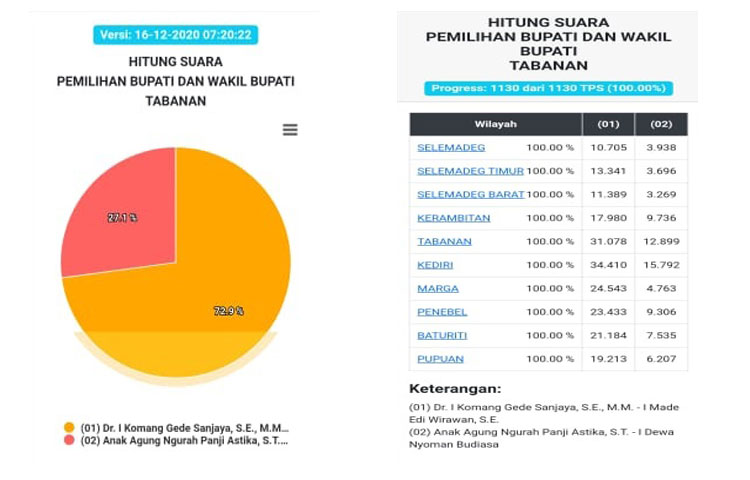































Komentar